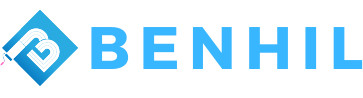Lewat
japri (jalur pribadi) Erlina bertanya padaku, ”Kenapa penampilanku tidak
terlihat lebih relijius, dibanding beberapa teman yang lain?”
Aku
sudah sering bergurau dengan perempuan yang menjadi teman satu grup WA
(whatsapp) alumni SMA (Sekolah Menengah Atas) itu, baik di grup atau lewat
japri. Tapi mendapat pertanyaan menyangkut spiritual yang pribadi seperti itu
membuatku sedikit mengantisipasi.
“Kamu
tidak ingin tahu,” ujarku bergurau.
“Tentu
saja, bro. Please tell me.”
Aku
paling tidak bisa kalau seorang wanita merajuk seperti itu. “It’s a long story.”
“I have a lot of time,” katanya disertai emoticon tersenyum malu.
Kemudian
aku bersiap menceritakan pada perempuan yang dulu paling cantik di kelas dan
salah satu bunga sekolah itu. Tentu saja Erlina makin cantik dan berisi saat
ini. Pesonanya masih membuat kaum Adam menoleh padanya.
Sengaja aku jawab pertanyaan Erlina dengan essay saja.
Dari
dulu aku selalu tertarik pada dua hal, sejarah dan teknologi dan sejarah. Lewat
sejarah, kita bisa belajar tentang masa lalu. Lewat teknologi, peradaban
manusia bisa menjadi lebih baik, lebih mudah, dan manusiawi.
Aku
membaca semua sejarah, baik nasional dan internasional.
Peristiwa
1965 membuatku sadar, bahwa agama sangat rentan dimanipulasi oleh kekuasaan.
Sampai umur sekitar 30 tahun, aku masih percaya kalau sejarah 1965 adalah
pertikaian golongan kanan dan kiri, yang kebetulan dimenangkan oleh golongan
pertama.
Negara
kita termasuk beruntung karena di Cina, Kamboja, dan Vietnam, golongan kiri
yang menang dan mengakibatkan pembantaian yang jumlahnya tidak terkira. Saat
itu, kuanggap sejarah tidak ubahnya hitam dan putih saja. Tapi aku curiga ada
yang tidak rapi di situ. Semacam chaos
theory, di mana sesuatu yang rapi pasti menyisakan ketidaksempurnaan.
Ternyata
benar. Dari banyak kesaksian pelaku dan korban 1965, banyak terjadi penyiksaan
dan penyimpangan pada peristiwa itu. Orang pribumi yang terkenal santun bisa
menjadi buas dan kesetanan saat membantai saudaranya. Semua itu digerakan oleh kemarahan
atas nama agama, baik Islam, Kristen, atau Hindu.
Apakah
hanya itu? Tidak.
Saya
beruntung pernah bekerja di sebuah yayasan pendidikan internasional, di mana
saya bertemu dengan banyak orang dari belahan dunia. Mereka banyak bercerita
tentang hal lain di luar sana.
Pernah
saya bertemu dengan seorang mantan militer dari Inggris yang pernah ditugaskan
di Sudan Selatan. Dia bercerita kalau di daerah yang sedang terjadi perang
saudara itu, para serdadu menyembelih tawanan perang yang nota bene masih satu
bangsa, sambil berteriak kebesaran Tuhan.
Hal
yang sama juga terjadi di Rwanda, Kongo, Afghanistan, Suriah, dan lain-lain. Konflik
perebutan kekuasaan selalu menggunakan agama untuk memicu kemarahan massa
secara kolektif (bersama-sama).
Manipulasi
kekuasaan menggunakan agama sangat efektif sekali. Orang yang jahat bisa
mencari ayat dan dalil untuk mencari pembenaran terhadap apa yang mereka
lakukan, baik pembunuhan massal, kekejaman, dan penyiksaan.
Segala
kengerian itu membuatku mengedepankan humanisme daripada agama. Humanity Above Religion. Orang bisa
berlaku kejam atas nama agama, tapi tidak dengan humanisme.
“Apa
itu humanisme?” Tanya Erlina singkat tapi antusias menunggu jawaban.
Humanisme
adalah sikap hidup yang demokratis dan etis yang menegaskan bahwa manusia
memiliki hak dan tanggung jawab untuk memberi makna bagi kehidupan yang lebih
baik.
Dengan
humanisme, kita bisa mengkoreksi anomali ajaran-ajaran yang bersifat absolut
dan tidak berperikemanusiaan. Ajaran itu bisa saja berbasis reliji (agama) atau
tidak sama sekali.
Jadi
humanis bukan anti reliji karena paham ini juga mengkonter semua ajaran dan
ideologi yang bersifat absolut.
Gus
Dur juga mengatakan, “memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya.
Merendahkan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya.”
“Dengan
humanisme, kita juga memuliakan Sang Pencipta. Itu sudah cukup bagiku tanpa
perlu terlihat berpenampilan relijius atau kelihatan alim,” ujarku menutup
penjelasan yang panjang.
“Oh
begitu. Aku paham sekarang,” sambut Erlina. “Kamu memang selalu berbeda dengan
yang lain. Sejak di bangku sekolah.”
Kuakhiri
japrian itu dengan berterima kasih. Kata orang dua kalimat terakhir itu adalah
pujian, tapi entahlah. [Benhil]