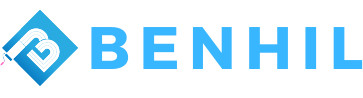Penggelut ilmu bahasa, psikolog atau siapa saja yang berminat menggumuli bahasa sebagai fenomena sosial dapat mengeksploitasi peranti berkomunikasi itu dari berbagai aspek. Salah satu aspek yang bisa diteliti adalah kadar kebahagiaan yang dikandung sebuah kata, yang didasarkan oleh penilaian dari pengguna bahasa bersangkutan.
Pada 1969, sejumlah psikolog di Universitas Illinois, Amerika Serikat, mencoba menemukan sisi positif dan negatif dari bahasa. Hasil penelitian itu antara lain menyebutkan bahwa para penutur semua bahasa cenderung memberikan konotasi positif atas kata-kata yang mereka gunakan.
Dari riset kebahasaan itulah muncul istilah Hipotesa Pollyanna. Disebut hipotesa karena penelitian itu masih perlu pengujian lewat penelitian lebih lanjut. Pollyanna adalah nama tokoh utama dalam novel karya Eleanor Porter. Sang protagonis adalah seorang gadis yang selalu berusaha melihat sisi-sisi positif dari setiap hal.
Hampir lima dekade setelah hipotesa itu dilahirkan, sebuah riset tentang sisi positif dan negatif dari kata di sejumlah bahasa dilakukan. Peter Dodds dari Universitas Vermont, yang menyelenggarakan penelitian itu, dengan menggunakan mega data, menemukan konklusi bahwa ada bahasa yang masuk kategori paling membahagikan, yang diraih oleh bahasa Spanyol dari 10 bahasa yang diteliti, dan ada bahasa yang paling kurang membahagiakan, yakni bahasa China. Bahasa Indonesia masuk di urutan keenam.
Metode penelitian itu cukup menarik. Peneliti mengumpulkan 100.000 kata-kata paling sering diujarkan dari masing-masing bahasa. Lalu meminta 50 orang penutur masing-masing bahasa untuk memberikan skor yang skalanya 1 hingga 10 untuk setiap kata. Kata yang dinilai punya nilai paling negatif memperoleh skor 1 dan untuk kata yang memberikan konotasi makna paling membahagiakan diberi skor 10.
Hasil pemberian skor itu kemudian dijadikan parameter untuk menentukan kadar kebahagiaan bahasa yang terdapat pada berbagai sumber pemakaian bahasa seperti media sosial, lirik lagu, teks percakapan pada film dan buku.
Penutur bahasa China boleh jadi kurang setuju dengan hasil riset itu. Sebab bahasanya berada di peringkat paling bawah. Penutur bahasa Indonesia, yang bahasanya di peringkat keenam, setelah Spanyol, Portugis, Inggris, Jerman dan Perancis, bolehlah tak reaktif menanggapi hasil riset itu.
Dalam khazanah teori tentang hubungan bahasa dan kebahagiaan, kata-kata yang diujarkan individu diakui berpengaruh secara psikis pada diri pengujar. Para psikolog bahkan menganjurkan individu yang ingin menikmati kebahagiaan dalam meniti kehidupan untuk sering-sering berpikir dan merasa dalam bingkai kosa kata yang mengusung makna rasa syukur atau terima kasih, keindahan, kebahagiaan, pemaafan, kesehatan, kekaguman, solusi, cinta, penerimaan, keberkahan, kebaikan, pengharapan, ketertarikan, kelucuan, dan peneguhan.
Tampaknya anjuran psikolog itu paralel dengan seruan profetik yang diafirmasi agama-agama. Ambil contoh, tentang kata syukur atau terima kasih. Individu yang sering mengucapkan kata-kata ini dipercaya memiliki rasa bahagia dalam hidupnya. Kenapa? Sebab dia cenderung menerima dengan lapang dada apa pun nasib yang ditimpakan Tuhan kepadanya. Dalam kata-kata kaum sufi, orang demikian akan berujar: saya akan tetap rendah hati ketika diguyur gelimang harta dan tak akan rendah diri ketika ditimpa kemiskinan.
Pemaafan adalah konsep yang muatan religiusnya cukup kental. Tuhan Maha Memaafkan, alangkah terpujinya jika sang ciptaan, yakni manusia yang tak lepas dari kekhilafan, juga memiliki watak pemaaf. Tindakan memaafkan berpengaruh pada psikis seseorang. Rasa lega, enteng di batin akan terasa kalau seseorang memaafkan lawannya ketimbang menyimpan dendam kesumat di kalbu.
Berpikir atau merasa sebagaimana yang dikandung oleh kata-kata yang dianjurkan oleh psikolog di atas memang dapat membangkitkan perasaan bahagia individu namun efeknya boleh jadi justru bertolak belakang jika kata-kata itu diobral oleh seorang pengarang dalam melahirkan karya seni, entah puisi atau prosa fiktif. Artinya, kata-kata yang berpotensi mengusung sisi kebahagiaan tak serta merta melahirkan karya yang indah, yang menjadi sumber lain kebahagiaan seseorang. Dalam konteks ini, kata-kata yang mengandung makna negatif, yang mengusung sisi kepedihan, kesedihan tak jarang juga bisa melahirkan keindahan. Mau bukti? Simaklah kisah-kisah Franz Kafka. Kisah-kisahnya muram, bicara tentang penderitaan manusia.
Kosa kata yang bertebaran justru bertolak belakang dengan anjuran sang psikolog di atas. Kelaparan, ketidakadilan, kesakitan, penantian tanpa harapan, kematian adalah konsep yang bertebaran di halaman-halaman fiksi pengarang Ceko yang menulis dalam bahasa Jerman itu. Namun dari sana, pembaca menghirup aroma esensial kehidupan.
Ketersohoran sang pengarang mengindikasikan banyaknya pengagum Kafka. Pembaca pun merasa bahagia membaca karya-karyanya. Itulah barangkali paradoks bahasa. Tuturan tentang kesengsaran pun melahirkan kebahagiaan.
Bukti lain adalah kata-kata positif yang memenuhi halaman novel-novel pop bagi pembaca tertentu justru melahirkan kebosanan. Tentu dalam hal ini berkecamuk subjektivitas dalam penilaian. Unsur subjektif selalu menggayuti penilaian tentang bahasa. Apa yang indah menurut seseorang tentang kata atau kosa kata bisa sangat berbeda buat yang lainnya.
Faktor subjektivitas penilaian atas fitur makna itu antara lain karena rapuhnya kesepakatan makna terhadap kata-kata tertentu oleh pengguna bahasa. Itu sebabnya unit pembentuk bahasa berpotensi berubah-ubah maknanya. Beberapa kata yang saat ini punya sifat makna yang positif sangat mungkin mengusung makna negatif pada satu generasi berikutnya. (M. Sunyoto)
Pada 1969, sejumlah psikolog di Universitas Illinois, Amerika Serikat, mencoba menemukan sisi positif dan negatif dari bahasa. Hasil penelitian itu antara lain menyebutkan bahwa para penutur semua bahasa cenderung memberikan konotasi positif atas kata-kata yang mereka gunakan.
Dari riset kebahasaan itulah muncul istilah Hipotesa Pollyanna. Disebut hipotesa karena penelitian itu masih perlu pengujian lewat penelitian lebih lanjut. Pollyanna adalah nama tokoh utama dalam novel karya Eleanor Porter. Sang protagonis adalah seorang gadis yang selalu berusaha melihat sisi-sisi positif dari setiap hal.
Hampir lima dekade setelah hipotesa itu dilahirkan, sebuah riset tentang sisi positif dan negatif dari kata di sejumlah bahasa dilakukan. Peter Dodds dari Universitas Vermont, yang menyelenggarakan penelitian itu, dengan menggunakan mega data, menemukan konklusi bahwa ada bahasa yang masuk kategori paling membahagikan, yang diraih oleh bahasa Spanyol dari 10 bahasa yang diteliti, dan ada bahasa yang paling kurang membahagiakan, yakni bahasa China. Bahasa Indonesia masuk di urutan keenam.
Metode penelitian itu cukup menarik. Peneliti mengumpulkan 100.000 kata-kata paling sering diujarkan dari masing-masing bahasa. Lalu meminta 50 orang penutur masing-masing bahasa untuk memberikan skor yang skalanya 1 hingga 10 untuk setiap kata. Kata yang dinilai punya nilai paling negatif memperoleh skor 1 dan untuk kata yang memberikan konotasi makna paling membahagiakan diberi skor 10.
Hasil pemberian skor itu kemudian dijadikan parameter untuk menentukan kadar kebahagiaan bahasa yang terdapat pada berbagai sumber pemakaian bahasa seperti media sosial, lirik lagu, teks percakapan pada film dan buku.
Penutur bahasa China boleh jadi kurang setuju dengan hasil riset itu. Sebab bahasanya berada di peringkat paling bawah. Penutur bahasa Indonesia, yang bahasanya di peringkat keenam, setelah Spanyol, Portugis, Inggris, Jerman dan Perancis, bolehlah tak reaktif menanggapi hasil riset itu.
Dalam khazanah teori tentang hubungan bahasa dan kebahagiaan, kata-kata yang diujarkan individu diakui berpengaruh secara psikis pada diri pengujar. Para psikolog bahkan menganjurkan individu yang ingin menikmati kebahagiaan dalam meniti kehidupan untuk sering-sering berpikir dan merasa dalam bingkai kosa kata yang mengusung makna rasa syukur atau terima kasih, keindahan, kebahagiaan, pemaafan, kesehatan, kekaguman, solusi, cinta, penerimaan, keberkahan, kebaikan, pengharapan, ketertarikan, kelucuan, dan peneguhan.
Tampaknya anjuran psikolog itu paralel dengan seruan profetik yang diafirmasi agama-agama. Ambil contoh, tentang kata syukur atau terima kasih. Individu yang sering mengucapkan kata-kata ini dipercaya memiliki rasa bahagia dalam hidupnya. Kenapa? Sebab dia cenderung menerima dengan lapang dada apa pun nasib yang ditimpakan Tuhan kepadanya. Dalam kata-kata kaum sufi, orang demikian akan berujar: saya akan tetap rendah hati ketika diguyur gelimang harta dan tak akan rendah diri ketika ditimpa kemiskinan.
Pemaafan adalah konsep yang muatan religiusnya cukup kental. Tuhan Maha Memaafkan, alangkah terpujinya jika sang ciptaan, yakni manusia yang tak lepas dari kekhilafan, juga memiliki watak pemaaf. Tindakan memaafkan berpengaruh pada psikis seseorang. Rasa lega, enteng di batin akan terasa kalau seseorang memaafkan lawannya ketimbang menyimpan dendam kesumat di kalbu.
Berpikir atau merasa sebagaimana yang dikandung oleh kata-kata yang dianjurkan oleh psikolog di atas memang dapat membangkitkan perasaan bahagia individu namun efeknya boleh jadi justru bertolak belakang jika kata-kata itu diobral oleh seorang pengarang dalam melahirkan karya seni, entah puisi atau prosa fiktif. Artinya, kata-kata yang berpotensi mengusung sisi kebahagiaan tak serta merta melahirkan karya yang indah, yang menjadi sumber lain kebahagiaan seseorang. Dalam konteks ini, kata-kata yang mengandung makna negatif, yang mengusung sisi kepedihan, kesedihan tak jarang juga bisa melahirkan keindahan. Mau bukti? Simaklah kisah-kisah Franz Kafka. Kisah-kisahnya muram, bicara tentang penderitaan manusia.
Kosa kata yang bertebaran justru bertolak belakang dengan anjuran sang psikolog di atas. Kelaparan, ketidakadilan, kesakitan, penantian tanpa harapan, kematian adalah konsep yang bertebaran di halaman-halaman fiksi pengarang Ceko yang menulis dalam bahasa Jerman itu. Namun dari sana, pembaca menghirup aroma esensial kehidupan.
Ketersohoran sang pengarang mengindikasikan banyaknya pengagum Kafka. Pembaca pun merasa bahagia membaca karya-karyanya. Itulah barangkali paradoks bahasa. Tuturan tentang kesengsaran pun melahirkan kebahagiaan.
Bukti lain adalah kata-kata positif yang memenuhi halaman novel-novel pop bagi pembaca tertentu justru melahirkan kebosanan. Tentu dalam hal ini berkecamuk subjektivitas dalam penilaian. Unsur subjektif selalu menggayuti penilaian tentang bahasa. Apa yang indah menurut seseorang tentang kata atau kosa kata bisa sangat berbeda buat yang lainnya.
Faktor subjektivitas penilaian atas fitur makna itu antara lain karena rapuhnya kesepakatan makna terhadap kata-kata tertentu oleh pengguna bahasa. Itu sebabnya unit pembentuk bahasa berpotensi berubah-ubah maknanya. Beberapa kata yang saat ini punya sifat makna yang positif sangat mungkin mengusung makna negatif pada satu generasi berikutnya. (M. Sunyoto)
Tags
Aktual