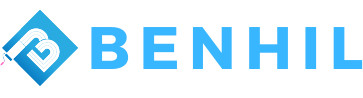Jakarta, 31/12 ( Benhil) - Pada tahun 2017 merupakan salah satu tahun bersejarah bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Sebanyak 101 daerah pada tahun ini menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk DKI Jakarta.
Meski hanya terjadi di tingkat provinsi, efeknya sangat besar hingga seantero negeri lantaran magnet Jakarta menjadi pusat perhatian publik.
Masih teringat jelas betapa isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tersebut mampu mengubah konstelasi politik Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Seorang calon petahana yang sedari awal tampak mustahil terkalahkan karena tingginya elektabiltas dan kekuatan dukungan politik partai-partai besar. Namun, karena kesalahannya sendiri, kemudian dipolitisasi sedemikian rupa, mampu tumbang tanpa diduga-duga. Peristiwa ini menjadi catatan penting bagi perjalanan demokrasi di Tanah Air, tidak hanya bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tetapi juga bagi partai politik, tokoh masyarakat, pemuka agama, serta anggota masyarakat lainnya.
Semestinya pemilu menjadi ajang pesta demokrasi yang menggembirakan, bukan ajang mempertebal perbedaan.
Pengamat politik Arif Susanto menyebut pada tahun 2017 adalah tahun politik yang diliputi kebencian. Perbedaan identitas dijadikan instrumen meraih kemenangan dalam politik elektoral. Perbedaan ini berdampak pada terpecahnya kelompok masyarakat yang dapat berakibat sangat buruk.
Arif menekankan isu SARA bisa saja terulang kembali dalam pilkada serentak pada tahun 2018 jika tidak ada upaya antisipasi dari seluruh pihak. Terlebih dalam pilkada mendatang terdapat 171 daerah yang akan menentukan pemimpinnya 5 tahun mendatang, di antaranya adalah provinsi dengan basis massa besar, seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.
Senada dengan Arif, pengamat politik Ray Rangkuti memprediksikan isu SARA masih berpotensi sebagai instrumen politik untuk menjatuhkan lawan dalam pilkada pada tahun depan.
SARA Lebih Berbahaya Bagi Ray, isu SARA ini lebih berbahaya daripada politik uang karena berdampak panjang. Ray menilai ada sejumlah sebab utama berkembangnya isu SARA dalam kontestasi politik, salah satunya ialah adanya suasana yang melegitimasi penggunaan isu itu.
Meskipun dalam pesta demokrasi pemilu isu SARA adalah hal yang dilarang, sejumlah anggota masyarakat menganggapnya sebagai hal yang lumrah karena mereka merasa tengah membela kepercayaannya. Hal ini kemudian menjadi sebuah kegamangan tersendiri.
Penyebab lainnya adalah tidak adanya interpretasi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan isu SARA itu sendiri. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jelas melarang praktik menghina etnik, agama, kelompok, serta masyarakat tetapi tidak jelas definisi dari penghinaan itu sendiri.
Faktor lainnya yakni masih lemahnya penindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti menggunakan isu SARA dalam kontestasi pemilu. Ray membandingkan dalam UU Pemilu, pelaku isu SARA hanya dikenai hukuman 1 tahun penjara, sedangkan dalam UU ITE, pengguna isu SARA bisa dijerat hingga 5 tahun penjara.
Akibatnya, tidak ada efek jera bagi para pelakunya. Atas dasar itu, dia memperkirakan isu SARA berpotensi digunakan kembali dalam Pilkada 2018, apalagi isu tersebut terbukti dapat mendongkrak atau menjatuhkan elektabilitas seseorang.
Pengamat politik Yusa Djuyandi menilai panasnya persaingan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta salah satunya disebabkan oleh politik akar rumput yang lebih bersifat ideologis dan idealis daripada di tataran elite yang lebih bersifat pragmatis. Sebagai buktinya, meskipun Golkar pada era kepemimpinan Setya Novanto, dan juga PPP mengubah haluan politiknya untuk lebih dekat dengan kubu pemerintah dan PDI Perjuangan, tidak serta-merta mengubah orientasi politik ideologis dan idealis arus bawah.
Dukungan Golkar dan PPP kepada Ahok dan Djarot hanya berada pada tataran elite yang bersifat pragmatis sebab elite hanya mempertimbangkan keuntungan dari besarnya potensi keterpilihan 46 s.d. 47 persen pasangan Ahok dan Djarot dalam berbagai hasil survei pra-pilkada.
Meskipun persaingan Pilgub DKI Jakarta bersifat lokal, nuansa persaingannya bersifat nasional. Menurut dia, fenomena politik yang muncul dalam pilkada itu justru tetap mempertegas masih adanya pertarungan dua pihak pendukung yang pernah saling berhadapan pada Pilpres 2014.
Adapun isu politik identitas yang kemudian muncul menurut Yusa sesungguhnya hanya merupakan dampak dari kesalahan retorika politik petahana. Kesalahan ini kemudian secara tidak langsung dimanfaatkan oleh pihak lawan politik.
Meski hanya terjadi di tingkat provinsi, efeknya sangat besar hingga seantero negeri lantaran magnet Jakarta menjadi pusat perhatian publik.
Masih teringat jelas betapa isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tersebut mampu mengubah konstelasi politik Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Seorang calon petahana yang sedari awal tampak mustahil terkalahkan karena tingginya elektabiltas dan kekuatan dukungan politik partai-partai besar. Namun, karena kesalahannya sendiri, kemudian dipolitisasi sedemikian rupa, mampu tumbang tanpa diduga-duga. Peristiwa ini menjadi catatan penting bagi perjalanan demokrasi di Tanah Air, tidak hanya bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tetapi juga bagi partai politik, tokoh masyarakat, pemuka agama, serta anggota masyarakat lainnya.
Semestinya pemilu menjadi ajang pesta demokrasi yang menggembirakan, bukan ajang mempertebal perbedaan.
Pengamat politik Arif Susanto menyebut pada tahun 2017 adalah tahun politik yang diliputi kebencian. Perbedaan identitas dijadikan instrumen meraih kemenangan dalam politik elektoral. Perbedaan ini berdampak pada terpecahnya kelompok masyarakat yang dapat berakibat sangat buruk.
Arif menekankan isu SARA bisa saja terulang kembali dalam pilkada serentak pada tahun 2018 jika tidak ada upaya antisipasi dari seluruh pihak. Terlebih dalam pilkada mendatang terdapat 171 daerah yang akan menentukan pemimpinnya 5 tahun mendatang, di antaranya adalah provinsi dengan basis massa besar, seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.
Senada dengan Arif, pengamat politik Ray Rangkuti memprediksikan isu SARA masih berpotensi sebagai instrumen politik untuk menjatuhkan lawan dalam pilkada pada tahun depan.
SARA Lebih Berbahaya Bagi Ray, isu SARA ini lebih berbahaya daripada politik uang karena berdampak panjang. Ray menilai ada sejumlah sebab utama berkembangnya isu SARA dalam kontestasi politik, salah satunya ialah adanya suasana yang melegitimasi penggunaan isu itu.
Meskipun dalam pesta demokrasi pemilu isu SARA adalah hal yang dilarang, sejumlah anggota masyarakat menganggapnya sebagai hal yang lumrah karena mereka merasa tengah membela kepercayaannya. Hal ini kemudian menjadi sebuah kegamangan tersendiri.
Penyebab lainnya adalah tidak adanya interpretasi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan isu SARA itu sendiri. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jelas melarang praktik menghina etnik, agama, kelompok, serta masyarakat tetapi tidak jelas definisi dari penghinaan itu sendiri.
Faktor lainnya yakni masih lemahnya penindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti menggunakan isu SARA dalam kontestasi pemilu. Ray membandingkan dalam UU Pemilu, pelaku isu SARA hanya dikenai hukuman 1 tahun penjara, sedangkan dalam UU ITE, pengguna isu SARA bisa dijerat hingga 5 tahun penjara.
Akibatnya, tidak ada efek jera bagi para pelakunya. Atas dasar itu, dia memperkirakan isu SARA berpotensi digunakan kembali dalam Pilkada 2018, apalagi isu tersebut terbukti dapat mendongkrak atau menjatuhkan elektabilitas seseorang.
Pengamat politik Yusa Djuyandi menilai panasnya persaingan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta salah satunya disebabkan oleh politik akar rumput yang lebih bersifat ideologis dan idealis daripada di tataran elite yang lebih bersifat pragmatis. Sebagai buktinya, meskipun Golkar pada era kepemimpinan Setya Novanto, dan juga PPP mengubah haluan politiknya untuk lebih dekat dengan kubu pemerintah dan PDI Perjuangan, tidak serta-merta mengubah orientasi politik ideologis dan idealis arus bawah.
Dukungan Golkar dan PPP kepada Ahok dan Djarot hanya berada pada tataran elite yang bersifat pragmatis sebab elite hanya mempertimbangkan keuntungan dari besarnya potensi keterpilihan 46 s.d. 47 persen pasangan Ahok dan Djarot dalam berbagai hasil survei pra-pilkada.
Meskipun persaingan Pilgub DKI Jakarta bersifat lokal, nuansa persaingannya bersifat nasional. Menurut dia, fenomena politik yang muncul dalam pilkada itu justru tetap mempertegas masih adanya pertarungan dua pihak pendukung yang pernah saling berhadapan pada Pilpres 2014.
Adapun isu politik identitas yang kemudian muncul menurut Yusa sesungguhnya hanya merupakan dampak dari kesalahan retorika politik petahana. Kesalahan ini kemudian secara tidak langsung dimanfaatkan oleh pihak lawan politik.
Keuntungan Kesalahan Politik
Hal yang tidak aneh jika dalam sebuah pilkada satu kubu atau pasangan mendapat keuntungan dari kesalahan politik lawannya. Soal adanya politik identitas, kemudian dimanfaatkan oleh kubu lain, lalu memunculkan kritik dari sebagian pihak, sesungguhnya hal itu telah ada sejak pilkada untuk pertama kalinya diselenggarakan.
Demokratisasi di tingkat lokal yang terwujud dalam pelaksanaan pilkada memang memberikan peluang bagi adanya sentimen identitas tertentu, dasarnya adalah keyakinan bahwa calon dari kelompoknya akan lebih memperhatikan nasib sesama. Oleh karena itu, sering kali masyarakat di daerah juga menjadi loyalis sejati dalam menghantarkan calonnya untuk menjadi kepala daerah, termasuk setelah kemenangan atau kekalahan itu sendiri.
Sementara itu, soal adanya kecurigaan bahwa pemanfaatan politik identitas di Jakarta akan memicu kerawanan konflik pilkada lainnya, Yusa mengatakan bahwa hal itu memang menjadi perhatian serius, terutama bila melihat Jakarta sebagai barometer demokrasi di Indonesia.
Akan tetapi, dia meyakini persoalan sosial politik identitas yang terjadi di Jakarta tidak akan meluas terbawa ke daerah dikarenakan adanya kondisi yang berbeda.
Kondisi di Jakarta menjadi berbeda karena ada kesalahan retorika politik yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Padahal, jika itu tidak terjadi, hasil dari beberapa lembaga survei yang mengatakan bahwa Ahok menang akan sangat besar peluangnya untuk terbukti. Ia menegaskan bahwa situasi politik dan koalisi politik akan selalu bersifat dinamis meski masih ada beberapa permasalahan dikotomi politik, seharusnya hal itu dapat disikapi secara dewasa. Dengan demikian, adanya perbedaan bukan untuk mencari perpecahan, melainkan mencari persamaan tujuan politik yang berorientasi pada kepentingan nasional yang lebih besar.
Di sisi lain, kondisi bangsa juga harus segera diperbaiki. Kecenderungan mendikotomikan pihak lain berdasarkan pada kelompok tertentu sebagai akibat dari pilkada sudah mulai harus dihentikan sebab negara ini perlu membangun. Pembangunan itu hanya dapat berhasil jika masyarakatnya bersatu.
Bila hal ini juga tidak kunjung terjadi, pada tahun depan bangsa dan negara ini akan dalam sebuah proses dinamika politik yang tidak sehat. (Ben/An)
Rangga Pandu Asmara Jingga
Demokratisasi di tingkat lokal yang terwujud dalam pelaksanaan pilkada memang memberikan peluang bagi adanya sentimen identitas tertentu, dasarnya adalah keyakinan bahwa calon dari kelompoknya akan lebih memperhatikan nasib sesama. Oleh karena itu, sering kali masyarakat di daerah juga menjadi loyalis sejati dalam menghantarkan calonnya untuk menjadi kepala daerah, termasuk setelah kemenangan atau kekalahan itu sendiri.
Sementara itu, soal adanya kecurigaan bahwa pemanfaatan politik identitas di Jakarta akan memicu kerawanan konflik pilkada lainnya, Yusa mengatakan bahwa hal itu memang menjadi perhatian serius, terutama bila melihat Jakarta sebagai barometer demokrasi di Indonesia.
Akan tetapi, dia meyakini persoalan sosial politik identitas yang terjadi di Jakarta tidak akan meluas terbawa ke daerah dikarenakan adanya kondisi yang berbeda.
Kondisi di Jakarta menjadi berbeda karena ada kesalahan retorika politik yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Padahal, jika itu tidak terjadi, hasil dari beberapa lembaga survei yang mengatakan bahwa Ahok menang akan sangat besar peluangnya untuk terbukti. Ia menegaskan bahwa situasi politik dan koalisi politik akan selalu bersifat dinamis meski masih ada beberapa permasalahan dikotomi politik, seharusnya hal itu dapat disikapi secara dewasa. Dengan demikian, adanya perbedaan bukan untuk mencari perpecahan, melainkan mencari persamaan tujuan politik yang berorientasi pada kepentingan nasional yang lebih besar.
Di sisi lain, kondisi bangsa juga harus segera diperbaiki. Kecenderungan mendikotomikan pihak lain berdasarkan pada kelompok tertentu sebagai akibat dari pilkada sudah mulai harus dihentikan sebab negara ini perlu membangun. Pembangunan itu hanya dapat berhasil jika masyarakatnya bersatu.
Bila hal ini juga tidak kunjung terjadi, pada tahun depan bangsa dan negara ini akan dalam sebuah proses dinamika politik yang tidak sehat. (Ben/An)
Rangga Pandu Asmara Jingga
Tags
Sosial Politik