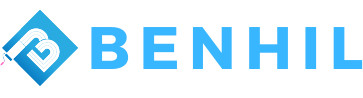Diberi mandat penuh sebagai formatur tunggal lewat forum Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar 2017, Airlangga Hartarto yang secara aklamasi terpilih sebagai orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin itu harus menyusun kepengurusan baru Dewan Pimpinan Pusat.
Di situlah Airlangga sedang diuji sejarah bagaimana dia memainkan peran sebagai orang nomor satu di parpol besar kedua setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam perpolitikan nasional.
Biasanya, seseorang yang diberi kekuasaan begitu besar akan menghadapi dua jalan bercabang yang akan menentukan kebesaran atau justru kekerdilannya sebagai aktor politik. Artinya, Airlangga bisa memilih orang-orang terbaik di Partai Golkar yang selama ini memperlihatkan kekritisan dan kapasitasnya sebagai kader atau memilih orang-orang medioker yang punya kepatuhan mutlak pada sang pemimpin.
Pemimpin modern yang mengagungkan rasionalitas akan memilih orang-orang jenis pertama. Pertimbangannya, organisasi partai harus dijalankan oleh orang-orang terpilih, yang bertanggung jawab dan sanggup menggerakkan roda organisasi atas inisiatif dan tanggung jawab personal mereka.
Namun pemimpin yang berwatak megalomania, menghendaki penyokong-penyokong yang setia, penurut dan menjalankan perintah sang pemimpin tanpa banyak cingcong, tanpa niat mempertanyakan argumentasi kebijakan sang bos.
Publik tentu berharap Airlangga adalah jenis pemimpin parpol yang berpikiran modern, memilih orang-orang terbaiknya, yang kritis demi kebesaran Partai Golkar. Memilih orang-orang demikian tentu bukan tanpa risiko. Setidaknya, proses politik dalam pengambilan kebijakan partai akan berjalan lebih lambat dan berbelit karena argumen yang ada harus diuji sebelum diterima sebagai kebijakan partai.
Namun, lebih penting dari hanya memilih dua jalan bercabang itu, Airlangga agaknya perlu menyadari sepenuhnya bahwa jalan sejarah yang sedang menantinya adalah menjawab pertanyaan berikut: bersediakah Airlangga menjadi sang pengambil kebijakan parpol yang bekerja cukup di balik layar alias panggung politik? Berperan sebagai orang di belakang layar itulah yang tak dimainkan Setya Novanto ketika dia diberi kepercayaan memimpin partai politik yang elektabilitasnya merosot di bawah kepemimpinannya itu.
Setya Novanto justru bernafsu ingin tampil atau berperan di mana-mana, di posisi-posisi yang dikiranya sangat strategis bagi kebesaran personalnya, namun akhirnya terbukti justru menjungkalkannya sebagai politikus secara tragis.
Ketika diberi kekuasaan sebagai orang nomor satu di tubuh Partai Golkar, Novanto merasa haus untuk menduduki jabatan yang lebih strategis lagi, yakni menjadi Ketua DPR. Visi politik Novanto ternyata sebatas pada kursi-kursi jabatan, tak sanggup memandang jauh yang melampaui kenikmatan sesaat berupa kue kekuasaan instan.
Airlangga tentu tak diharapkan menapaki jejak Novanto yang tragis itu. Sekalipun putra teknokrat Hartarto itu dengan mudah bisa memilih untuk menjadi Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar sebagaimana yang dialami Novanto di hari-hari akhir kekuasaannya, membiarkan jabatan Ketua DPR dijabat kader lain Partai Golkar akan lebih baik.
Keputusan Airlangga untuk memilih berperan di belakang layar itulah tampaknya yang perlu dilakukan dengan keteguhan hati. Sayangnya, keteguhan itu belum tampak pada hari-hari pertama dia terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Ketika jurnalis bertanya apakah dia akan tetap menjabat sebagai Menteri Perindustrian setelah ditetapkan oleh forum Munaslub Partai Golkar sebagai Ketua Umum DPP, Airlangga menjawab secara kurang tegas. Katanya, "Semua itu tergantung Presiden Joko Widodo." Sudah saatnya Airlangga menyadari bahwa sebagai orang nomor satu di parpol besar, posisi politik sangat strategis dan bukan lagi nasibnya ditentukan oleh Presiden yang memakai tenaga dan pikirannya sebagai salah satu pembantu Presiden.
Dengan kesadaran dan kebanggaan penuh sebagai orang nomor satu di Partai Golkar, layaklah jika Airlangga segera memutuskan untuk tidak lagi menjadi menteri. Publik pun akan memandangnya sebagai sosok yang setara dengan prestise bos PDIP Megawati Soekarnoputri dan bos Partai Gerindra Prabowo Subianto atau bos Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Airlangga tak perlu menyibukkan diri memimpin DPR seperti Novanto. Tapi dia sudah saatnya menjadi penentu siapa orang-orang Partai Golkar yang harus tampil sebagai kandidat dalam Pilkada 2018 atau capres yang mendapingi petahana dalam Pilpres 2019. Menjadi "king maker", itulah posisi yang layak disandang Airlangga, yang sebelumnya sudah dimaninkan sosok-sosok di balik layar, seperti Mega, Prabowo dan SBY.
Menjadi bos yang menentukan arah ke mana Partai Golkar bergerak di pusaran Pilkada Serentak 2018 dan mempersiapkan Golkar di Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 jauh lebih penting dan strategis bagi Airlangga. Tentu pilihan peran itu punya risiko finansial yang tak mudah dipecahkan, yang Novanto sendiri tak mampu memecahkannya sehingga dia memilih untuk menjadi Ketua DPR dengan menerima gaji dan berbagai previlise, yang tak bisa diperolehnya hanya dengan menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Meninggalkan posisi sebagai Menteri Perindustrian dan hanya bekerja di Kantor DPP Partai Golkar tentu tak memberikan banyak kemanfaatan material lagi. Namun, justru di sinilah tantangan sejarah yang harus dijawab oleh Airlangga, yang ketika dia berhasil melewatinya, sejarah pun akan mengganjarnya dengan kebesaran yang sepadan. Setidaknya, bukan mustahil bila kelak Airlangga berhasil membangun citra positif sebagai bos Partai Golkar yang bersih dan layak dicalonkan sebagai orang nomor satu dalam Pilpres 2024. (Ben/An/M. Sunyoto)
Di situlah Airlangga sedang diuji sejarah bagaimana dia memainkan peran sebagai orang nomor satu di parpol besar kedua setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam perpolitikan nasional.
Biasanya, seseorang yang diberi kekuasaan begitu besar akan menghadapi dua jalan bercabang yang akan menentukan kebesaran atau justru kekerdilannya sebagai aktor politik. Artinya, Airlangga bisa memilih orang-orang terbaik di Partai Golkar yang selama ini memperlihatkan kekritisan dan kapasitasnya sebagai kader atau memilih orang-orang medioker yang punya kepatuhan mutlak pada sang pemimpin.
Pemimpin modern yang mengagungkan rasionalitas akan memilih orang-orang jenis pertama. Pertimbangannya, organisasi partai harus dijalankan oleh orang-orang terpilih, yang bertanggung jawab dan sanggup menggerakkan roda organisasi atas inisiatif dan tanggung jawab personal mereka.
Namun pemimpin yang berwatak megalomania, menghendaki penyokong-penyokong yang setia, penurut dan menjalankan perintah sang pemimpin tanpa banyak cingcong, tanpa niat mempertanyakan argumentasi kebijakan sang bos.
Publik tentu berharap Airlangga adalah jenis pemimpin parpol yang berpikiran modern, memilih orang-orang terbaiknya, yang kritis demi kebesaran Partai Golkar. Memilih orang-orang demikian tentu bukan tanpa risiko. Setidaknya, proses politik dalam pengambilan kebijakan partai akan berjalan lebih lambat dan berbelit karena argumen yang ada harus diuji sebelum diterima sebagai kebijakan partai.
Namun, lebih penting dari hanya memilih dua jalan bercabang itu, Airlangga agaknya perlu menyadari sepenuhnya bahwa jalan sejarah yang sedang menantinya adalah menjawab pertanyaan berikut: bersediakah Airlangga menjadi sang pengambil kebijakan parpol yang bekerja cukup di balik layar alias panggung politik? Berperan sebagai orang di belakang layar itulah yang tak dimainkan Setya Novanto ketika dia diberi kepercayaan memimpin partai politik yang elektabilitasnya merosot di bawah kepemimpinannya itu.
Setya Novanto justru bernafsu ingin tampil atau berperan di mana-mana, di posisi-posisi yang dikiranya sangat strategis bagi kebesaran personalnya, namun akhirnya terbukti justru menjungkalkannya sebagai politikus secara tragis.
Ketika diberi kekuasaan sebagai orang nomor satu di tubuh Partai Golkar, Novanto merasa haus untuk menduduki jabatan yang lebih strategis lagi, yakni menjadi Ketua DPR. Visi politik Novanto ternyata sebatas pada kursi-kursi jabatan, tak sanggup memandang jauh yang melampaui kenikmatan sesaat berupa kue kekuasaan instan.
Airlangga tentu tak diharapkan menapaki jejak Novanto yang tragis itu. Sekalipun putra teknokrat Hartarto itu dengan mudah bisa memilih untuk menjadi Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar sebagaimana yang dialami Novanto di hari-hari akhir kekuasaannya, membiarkan jabatan Ketua DPR dijabat kader lain Partai Golkar akan lebih baik.
Keputusan Airlangga untuk memilih berperan di belakang layar itulah tampaknya yang perlu dilakukan dengan keteguhan hati. Sayangnya, keteguhan itu belum tampak pada hari-hari pertama dia terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Ketika jurnalis bertanya apakah dia akan tetap menjabat sebagai Menteri Perindustrian setelah ditetapkan oleh forum Munaslub Partai Golkar sebagai Ketua Umum DPP, Airlangga menjawab secara kurang tegas. Katanya, "Semua itu tergantung Presiden Joko Widodo." Sudah saatnya Airlangga menyadari bahwa sebagai orang nomor satu di parpol besar, posisi politik sangat strategis dan bukan lagi nasibnya ditentukan oleh Presiden yang memakai tenaga dan pikirannya sebagai salah satu pembantu Presiden.
Dengan kesadaran dan kebanggaan penuh sebagai orang nomor satu di Partai Golkar, layaklah jika Airlangga segera memutuskan untuk tidak lagi menjadi menteri. Publik pun akan memandangnya sebagai sosok yang setara dengan prestise bos PDIP Megawati Soekarnoputri dan bos Partai Gerindra Prabowo Subianto atau bos Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Airlangga tak perlu menyibukkan diri memimpin DPR seperti Novanto. Tapi dia sudah saatnya menjadi penentu siapa orang-orang Partai Golkar yang harus tampil sebagai kandidat dalam Pilkada 2018 atau capres yang mendapingi petahana dalam Pilpres 2019. Menjadi "king maker", itulah posisi yang layak disandang Airlangga, yang sebelumnya sudah dimaninkan sosok-sosok di balik layar, seperti Mega, Prabowo dan SBY.
Menjadi bos yang menentukan arah ke mana Partai Golkar bergerak di pusaran Pilkada Serentak 2018 dan mempersiapkan Golkar di Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 jauh lebih penting dan strategis bagi Airlangga. Tentu pilihan peran itu punya risiko finansial yang tak mudah dipecahkan, yang Novanto sendiri tak mampu memecahkannya sehingga dia memilih untuk menjadi Ketua DPR dengan menerima gaji dan berbagai previlise, yang tak bisa diperolehnya hanya dengan menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Meninggalkan posisi sebagai Menteri Perindustrian dan hanya bekerja di Kantor DPP Partai Golkar tentu tak memberikan banyak kemanfaatan material lagi. Namun, justru di sinilah tantangan sejarah yang harus dijawab oleh Airlangga, yang ketika dia berhasil melewatinya, sejarah pun akan mengganjarnya dengan kebesaran yang sepadan. Setidaknya, bukan mustahil bila kelak Airlangga berhasil membangun citra positif sebagai bos Partai Golkar yang bersih dan layak dicalonkan sebagai orang nomor satu dalam Pilpres 2024. (Ben/An/M. Sunyoto)
Tags
Sosial Politik