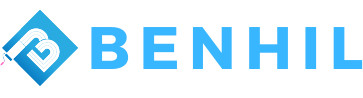Setelah
menggaungkan semboyan NKRI Harga Mati, publik tampaknya perlu
memopulerkan tekad serupa dalam praktis berpolitik: Demokrasi Harga
Mati.
Tentu tak perlu diberi adjektiva di belakang kata demokrasi, seperti ketika Orde Baru (Orba) menggunakannya dengan merek Demokrasi Pancasila atau negeri-negeri sosialis yang menggunakan cap Demokrasi Rakyat.
Demokrasi tanpa adjektiva tentulah sudah memadai untuk mengacu pada sistem politik yang menempatkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat.
Menggaungkan demokrasi sebagai harga mati yang tak bisa ditawar tampaknya perlu mengingat di beberapa kesempatan dan di beberapa benak tokoh tertentu masih saja muncul kehendak untuk mencoba mewacanakan sistem politik alternatif yang secara tak terang-benderang bertentangan dengan prinsip demokrasi.
Demokrasi bukan sekadar diejahwantakan dalam bentuk pemilihan umum dalam menentukan kepemimpinan politik suatu bangsa. Demokrasi juga menafikkan pejabat militer untuk berbicara di muka umum berbincang tentang kekuasaan politik, apa pun niat dan tujuan dalam perbincangan itu.
Panglima perang tak lebih dari petugas ketentaraan yang mengikuti apa kata panglima tertinggi yang posisinya dipegang oleh presiden. Demokrasi Pancasila yang didaku oleh Orde Baru sebagai demokrasi khas Indonesia dengan memberikan fungsi politis kepada institusi ketentaraan adalah sistem demokrasi yang distortif.
Reformasi 1998 telah meluruskan distorsi itu. Harus diakui, demokrasi bukanlah sistem yang sempurna yang sanggup menyejahterakan semua warga masyarakat. Selalu ada yang menjadi pecundang, termasuk mereka yang gagal dalam meraih peruntungan dalam hidup sehari-hari.
Tak jarang ada tokoh politik yang melakukan kritik dengan mengatakan bahwa jika demokrasi tak mampu menyejahterakan masyarakat, itu berarti praktik demokrasi selama ini berjalan tidak benar, melenceng dari cita-cita demokrasi.
Kritik semacam itu boleh jadi mengandung beberapa persen kebenaran. Sekalipun demikian, fenomena ketimpangan yang ditandai oleh sebagian kalangan yang sukses menyejahterakan diri dan sebagian yang gagal memengentaskan diri dari kemelaratan material dalam sistem demokrasi tetap saja mengandung keutamaan dibandingkan dalam sistem otoritarian.
Kenapa? Karena dalam sistem demokrasi, publik diberi peluang relatif sama dalam bentuk informasi yang terbuka dalam meraih keberhasilan. Dalam sistem yang dikuasai oleh otokrat, mereka yang sejahtera adalah yang mendukung sang penguasa, sementara lawan-lawan politik dibikin sulit untuk menyejahterakan diri.
Dalam sistem demokrasi, pemenang dan pecundang dalam perebutan kekuasaan politik bisa bergantian. Ini jelas berkah demokrasi yang tak bisa dicari dalam otoritarianisme Orba yang berkuasa lebih dari tiga dekade dengan pemain tunggal dan konco-konconya yang menumpas setiap kekuatan politik yang muncul dari kalangan oposisi.
Yang musykil, fakta-fakta semacam ini kadang terlupakan oleh kalangan yang masih merindukan kembalinya seorang penguasa yang dianggap sebagai orang kuat, yang bisa secara efektif menghentikan segala bentuk kegaduhan yang oleh beberapa kalangan dianggap merugikan proses berpolitik.
Kegaduhan dalam demokrasi, selama tak didikuti oleh destruksi alias kekerasan fisik masih ditenggang. Pada titik ini, kekurangan fundamental praktik demokrasi di Tanah Air sebetulnya bukan pada gagalnya sistem itu menyejahterakan seluruh warga negara tapi belum berfungsinya institusi penegak hukum, dalam hal ini institusi kepolisian, untuk menegakkan prinsip-prinsip berdemokrasi.
Dalam banyak kasus, tindakan hukum dengan menggunakan kekuasaan paksa tak dilakukan polisi terhadap mereka yang mencederai praktik demokrasi. Diskusi politik atau ilmiah di tempat tertutup pun bisa diganggu oleh kekuatan sipil anarkis. Bukannya kaum anarkis yang ditangkap, diadili dan dipenjara karena melanggar undang-undang tapi aktivitas diskusi itu yang dibubarkan demi keamanan.
Tentu diskusi yang paling halal untuk dirusuhi oleh kelompok sosial tertentu adalah yang mengambil tema politik kiri, apalagi jika haluan kiri itu diberi label 1965, yang merupakan momen berdarah-darah yang digunakan sebagai argumen melegitimasikan kediktatoran sang penguasa, untuk menancapkan kuku otoriterianisme di Tanah Air.
Menggaungkan bertubi-tubi semboyan Demokrasi Harga Mati tentu perlu dibarengi dengan langkah-langkah konkret pemerintah, terutama dalam memastikan bahwa institusi kepolisian bekerja sesuai dengan prinsip demokrasi.
Pokok masalah selama ini justru pada penegakkan hukum oleh polisi terhadap massa yang melakukan aksi tak demokratis. Kalangan pegiat hak asasi manusia menyatakan bahwa di sisa pemerintahannya yang kurang lebih dua tahun ini selayaknya Presiden Joko Widodo memberikan perhatian yang memadai pada penegakan hukum.
Terlalu fokus ke pembangunan fisik infrastruktur tak ada buruknya selama tidak mengabaikan kebutuhan terhadap penegakan hukum. Dengan legitimasi politik yang tetap kokoh, sebagaimana diperlihatkan lewat hasil jajak pendapat sejumlah lembaga survei, mayoritas masyarakat puas pemerintahan Jokowi. Joko Widodo tak perlu bimbang untuk memerintahkan polisi menangkap dan membawa ke meja hijau para perusuh yang membubarkan diskusi politik di tempat tertutup maupun terbuka.
Yang ironis, para politisi sejumlah parpol yang kebetulan berhaluan ideologis berbeda dengan penyelenggara diskusi tidak memperlihatkan sikap demokratisnya dalam kasus pembubaran diskusi itu.
Suara serempak untuk memastikan bahwa demokrasi sebagai sistem yang tak bisa diubah-ibah alias harga mati perlu juga dilakukan oleh politisi dari parpol apa pun, yang eksistensinya dimungkinkan karena berkah demokrasi itu sendiri.
Itu artinya, semua politisi dari parpol apa pun perlu mengutuk bersama-sama terhadap kelompok masyarakat yang berbuat rusuh dalam usaha membubarkan sebuah percakapan demokratis dengan tema apa pun.
Tentu tak perlu diberi adjektiva di belakang kata demokrasi, seperti ketika Orde Baru (Orba) menggunakannya dengan merek Demokrasi Pancasila atau negeri-negeri sosialis yang menggunakan cap Demokrasi Rakyat.
Demokrasi tanpa adjektiva tentulah sudah memadai untuk mengacu pada sistem politik yang menempatkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat.
Menggaungkan demokrasi sebagai harga mati yang tak bisa ditawar tampaknya perlu mengingat di beberapa kesempatan dan di beberapa benak tokoh tertentu masih saja muncul kehendak untuk mencoba mewacanakan sistem politik alternatif yang secara tak terang-benderang bertentangan dengan prinsip demokrasi.
Demokrasi bukan sekadar diejahwantakan dalam bentuk pemilihan umum dalam menentukan kepemimpinan politik suatu bangsa. Demokrasi juga menafikkan pejabat militer untuk berbicara di muka umum berbincang tentang kekuasaan politik, apa pun niat dan tujuan dalam perbincangan itu.
Panglima perang tak lebih dari petugas ketentaraan yang mengikuti apa kata panglima tertinggi yang posisinya dipegang oleh presiden. Demokrasi Pancasila yang didaku oleh Orde Baru sebagai demokrasi khas Indonesia dengan memberikan fungsi politis kepada institusi ketentaraan adalah sistem demokrasi yang distortif.
Reformasi 1998 telah meluruskan distorsi itu. Harus diakui, demokrasi bukanlah sistem yang sempurna yang sanggup menyejahterakan semua warga masyarakat. Selalu ada yang menjadi pecundang, termasuk mereka yang gagal dalam meraih peruntungan dalam hidup sehari-hari.
Tak jarang ada tokoh politik yang melakukan kritik dengan mengatakan bahwa jika demokrasi tak mampu menyejahterakan masyarakat, itu berarti praktik demokrasi selama ini berjalan tidak benar, melenceng dari cita-cita demokrasi.
Kritik semacam itu boleh jadi mengandung beberapa persen kebenaran. Sekalipun demikian, fenomena ketimpangan yang ditandai oleh sebagian kalangan yang sukses menyejahterakan diri dan sebagian yang gagal memengentaskan diri dari kemelaratan material dalam sistem demokrasi tetap saja mengandung keutamaan dibandingkan dalam sistem otoritarian.
Kenapa? Karena dalam sistem demokrasi, publik diberi peluang relatif sama dalam bentuk informasi yang terbuka dalam meraih keberhasilan. Dalam sistem yang dikuasai oleh otokrat, mereka yang sejahtera adalah yang mendukung sang penguasa, sementara lawan-lawan politik dibikin sulit untuk menyejahterakan diri.
Dalam sistem demokrasi, pemenang dan pecundang dalam perebutan kekuasaan politik bisa bergantian. Ini jelas berkah demokrasi yang tak bisa dicari dalam otoritarianisme Orba yang berkuasa lebih dari tiga dekade dengan pemain tunggal dan konco-konconya yang menumpas setiap kekuatan politik yang muncul dari kalangan oposisi.
Yang musykil, fakta-fakta semacam ini kadang terlupakan oleh kalangan yang masih merindukan kembalinya seorang penguasa yang dianggap sebagai orang kuat, yang bisa secara efektif menghentikan segala bentuk kegaduhan yang oleh beberapa kalangan dianggap merugikan proses berpolitik.
Kegaduhan dalam demokrasi, selama tak didikuti oleh destruksi alias kekerasan fisik masih ditenggang. Pada titik ini, kekurangan fundamental praktik demokrasi di Tanah Air sebetulnya bukan pada gagalnya sistem itu menyejahterakan seluruh warga negara tapi belum berfungsinya institusi penegak hukum, dalam hal ini institusi kepolisian, untuk menegakkan prinsip-prinsip berdemokrasi.
Dalam banyak kasus, tindakan hukum dengan menggunakan kekuasaan paksa tak dilakukan polisi terhadap mereka yang mencederai praktik demokrasi. Diskusi politik atau ilmiah di tempat tertutup pun bisa diganggu oleh kekuatan sipil anarkis. Bukannya kaum anarkis yang ditangkap, diadili dan dipenjara karena melanggar undang-undang tapi aktivitas diskusi itu yang dibubarkan demi keamanan.
Tentu diskusi yang paling halal untuk dirusuhi oleh kelompok sosial tertentu adalah yang mengambil tema politik kiri, apalagi jika haluan kiri itu diberi label 1965, yang merupakan momen berdarah-darah yang digunakan sebagai argumen melegitimasikan kediktatoran sang penguasa, untuk menancapkan kuku otoriterianisme di Tanah Air.
Menggaungkan bertubi-tubi semboyan Demokrasi Harga Mati tentu perlu dibarengi dengan langkah-langkah konkret pemerintah, terutama dalam memastikan bahwa institusi kepolisian bekerja sesuai dengan prinsip demokrasi.
Pokok masalah selama ini justru pada penegakkan hukum oleh polisi terhadap massa yang melakukan aksi tak demokratis. Kalangan pegiat hak asasi manusia menyatakan bahwa di sisa pemerintahannya yang kurang lebih dua tahun ini selayaknya Presiden Joko Widodo memberikan perhatian yang memadai pada penegakan hukum.
Terlalu fokus ke pembangunan fisik infrastruktur tak ada buruknya selama tidak mengabaikan kebutuhan terhadap penegakan hukum. Dengan legitimasi politik yang tetap kokoh, sebagaimana diperlihatkan lewat hasil jajak pendapat sejumlah lembaga survei, mayoritas masyarakat puas pemerintahan Jokowi. Joko Widodo tak perlu bimbang untuk memerintahkan polisi menangkap dan membawa ke meja hijau para perusuh yang membubarkan diskusi politik di tempat tertutup maupun terbuka.
Yang ironis, para politisi sejumlah parpol yang kebetulan berhaluan ideologis berbeda dengan penyelenggara diskusi tidak memperlihatkan sikap demokratisnya dalam kasus pembubaran diskusi itu.
Suara serempak untuk memastikan bahwa demokrasi sebagai sistem yang tak bisa diubah-ibah alias harga mati perlu juga dilakukan oleh politisi dari parpol apa pun, yang eksistensinya dimungkinkan karena berkah demokrasi itu sendiri.
Itu artinya, semua politisi dari parpol apa pun perlu mengutuk bersama-sama terhadap kelompok masyarakat yang berbuat rusuh dalam usaha membubarkan sebuah percakapan demokratis dengan tema apa pun.
M. Sunyoto
Tags
Sosial Politik