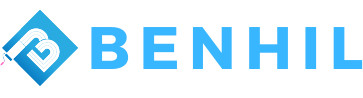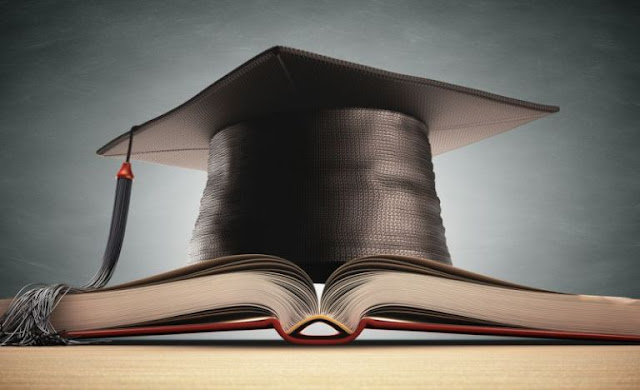Ketika seorang akademikus dari sebuah universitas terkemuka di Ibu Kota menulis bahwa seorang pemimpin politik yang sedang disanjung pendukungnya sebetulnya tak punya pikiran-pikiran yang pantas dibanggakan, akademikus yang mengampu studi filsafat itu sedang mengajak berpolemik.
Agar tak penasaran, perlulah menyebut identitas sang akademikus: Rocky Gerung. Sindiran-sindiriannya di akun Twitternya menyasar siapa lagi kalau bukan pemimpin potitik paling merakyat saat ini: Presiden Joko Widodo.
Rocky yang belajar filsafat tampaknya punya penilaian yang simplistik bahwa kehebatan seorang pemimpin politik diukur dari keluasan dan kedalaman pemikirannya, kesanggupannya menelurkan pikiran-pikiran bernas, inovatif dan kreatif layaknya Voltaire, cendekiawan filsuf yang lebih banyak bertungkus-lumus dalam dunia ide-ide, bukan pemimpin yang waktu dan tenaganya banyak dihabiskan berinteraksi dengan masyarakat.
Latar belakang demikian jelas bertolak belakang dengan pengalaman mereka yang banyak menghabiskan waktunya menekuni bidang studi yang condong pada pengetahuan terapan seperti yang dimiliki Jokowi.
Menilai Jokowi, yang berlatar pendidikan studi kehutanan, dengan takaran seberapa berbobot gagasan-gagasan yang dilontarkannya ketika menduduki kursi kepresidenan bukanlah sikap yang adil, sekali pun sebagai warga negara biasa sang penilai punya hak untuk menuntut pemimpinnya punya kualifikasi di ranah pemikiran filosofis.
Tentu saja, tak perlu dinafikkan bahwa presiden yang berpikiran cemerlang dapat menginspirasi warga, kalangan anak muda yang punya kecenderungan memanfaatkan waktunya dalam olah pikir, bukan olah tangan dan kaki.
Namun yang luput, atau sengaja memilih luput, dari perhatian Rocky Gerung adalah sisi kehebatan manusiawi yang ini: bahwa keistimewaan seorang pemimpin politik bisa ditakar dari kesanggupannya untuk tetap menjadi dirinya sendiri, baik saat belum memiliki kekuasaan, atau saat memiliki kekuasaan, tapi belum begitu signifikan maupun saat gunung kekuasaan itu ada di tangan.
Di titik inilah salah satu kesistimewaan seorang pemimpin politik bisa diukur: bertambahnya kekuasaan tak mengubah jati diri personal. Kekuasaan tak menyeretnya untuk cenderung korup.
Barangkali akan lebih kritis kontekstual jika #RockyGerung mengarahkan kritiknya kepada Jokowi pada sisi otentitas sikap merakyatnya yang diperlihatkan media massa, bukannya mengukur kecemerlangan pikiran-pikirannya.
Sebab, sejak televisi, medium pandang-dengar yang paling mudah dan serta-merta membuat perasaan pemirsa terharu biru, dimanfaatkan untuk kampanye politik, otentitas perilaku watak tokoh publik perlu dipertanyakan terus-menerus.
Ronald Reagan yang dari segi pemikiran jauh di bawah pesaing-pesaing politiknya dalam kontes merebut kursi kepresidenan di AS akhirnya menang berkat para manajer dalam tim sukses kampanyenya, yang memanfaatkan televisi untuk membujuk warga AS terpesona oleh Reagan.
Kesahajaan yang diperlihatkan lewat liputan media massa terhadap Jokowi jelas memiliki nilai inspiratif. Artinya, hidup sederhana adalah keutamaan, apalagi di zaman ketika kesintasan lingkungan hidup yang sehat menjadi pertaruhan hidup-mati masa depan anak cucu.
Ketika Jokowi memperlihatkan kepada publik bahwa dia sedang menikmati masakan di warung lalu bersenandung bersama para penyanyi jalanan dalam interaksi yang guyub, sinyal yang ditebarkan Jokowi adalah: kebahagiaan itu murah untuk meraihnya, tak mesti memperolehnya di tempat eksklusif dan di kancah musisi elitis.
Tentu semua kiprah pamer kesederhanaan bukan yang paling signifikan dari seorang pemimpin politik. Semua itu bisa dikemas oleh sutradara. Yang esensial dari seorang pemimpin jelas kesanggupannya untuk merealisasikan keadilan di tengan tarik-menarik kepentingan yang bertabrakan di hadapan sang pemimpin.
Ketika sang pemimpin berani menampik bujukan kelompok elite paling berpengaruh untuk meluluskan kepentingan mereka dan konsisten meluluskan kepentingan rakyat yang terpinggirkan karena tak punya suara dan daya membujuk, saat itulah keistimewaan pemimpin yang sejati mulai mengejawantah.
Namun politik tak beroperasi dalam mekanisme yang simplistik lurus lempang. Kebijakan yang prorakyat kecil pun bisa menjadi jalan masuk bagi kaum elite untuk menikmati alokasi dana yang dijatahkan buat rakyat kecil kebanyakan.
Agar tak penasaran, perlulah menyebut identitas sang akademikus: Rocky Gerung. Sindiran-sindiriannya di akun Twitternya menyasar siapa lagi kalau bukan pemimpin potitik paling merakyat saat ini: Presiden Joko Widodo.
Rocky yang belajar filsafat tampaknya punya penilaian yang simplistik bahwa kehebatan seorang pemimpin politik diukur dari keluasan dan kedalaman pemikirannya, kesanggupannya menelurkan pikiran-pikiran bernas, inovatif dan kreatif layaknya Voltaire, cendekiawan filsuf yang lebih banyak bertungkus-lumus dalam dunia ide-ide, bukan pemimpin yang waktu dan tenaganya banyak dihabiskan berinteraksi dengan masyarakat.
Latar belakang demikian jelas bertolak belakang dengan pengalaman mereka yang banyak menghabiskan waktunya menekuni bidang studi yang condong pada pengetahuan terapan seperti yang dimiliki Jokowi.
Menilai Jokowi, yang berlatar pendidikan studi kehutanan, dengan takaran seberapa berbobot gagasan-gagasan yang dilontarkannya ketika menduduki kursi kepresidenan bukanlah sikap yang adil, sekali pun sebagai warga negara biasa sang penilai punya hak untuk menuntut pemimpinnya punya kualifikasi di ranah pemikiran filosofis.
Tentu saja, tak perlu dinafikkan bahwa presiden yang berpikiran cemerlang dapat menginspirasi warga, kalangan anak muda yang punya kecenderungan memanfaatkan waktunya dalam olah pikir, bukan olah tangan dan kaki.
Namun yang luput, atau sengaja memilih luput, dari perhatian Rocky Gerung adalah sisi kehebatan manusiawi yang ini: bahwa keistimewaan seorang pemimpin politik bisa ditakar dari kesanggupannya untuk tetap menjadi dirinya sendiri, baik saat belum memiliki kekuasaan, atau saat memiliki kekuasaan, tapi belum begitu signifikan maupun saat gunung kekuasaan itu ada di tangan.
Di titik inilah salah satu kesistimewaan seorang pemimpin politik bisa diukur: bertambahnya kekuasaan tak mengubah jati diri personal. Kekuasaan tak menyeretnya untuk cenderung korup.
Barangkali akan lebih kritis kontekstual jika #RockyGerung mengarahkan kritiknya kepada Jokowi pada sisi otentitas sikap merakyatnya yang diperlihatkan media massa, bukannya mengukur kecemerlangan pikiran-pikirannya.
Sebab, sejak televisi, medium pandang-dengar yang paling mudah dan serta-merta membuat perasaan pemirsa terharu biru, dimanfaatkan untuk kampanye politik, otentitas perilaku watak tokoh publik perlu dipertanyakan terus-menerus.
Ronald Reagan yang dari segi pemikiran jauh di bawah pesaing-pesaing politiknya dalam kontes merebut kursi kepresidenan di AS akhirnya menang berkat para manajer dalam tim sukses kampanyenya, yang memanfaatkan televisi untuk membujuk warga AS terpesona oleh Reagan.
Kesahajaan yang diperlihatkan lewat liputan media massa terhadap Jokowi jelas memiliki nilai inspiratif. Artinya, hidup sederhana adalah keutamaan, apalagi di zaman ketika kesintasan lingkungan hidup yang sehat menjadi pertaruhan hidup-mati masa depan anak cucu.
Ketika Jokowi memperlihatkan kepada publik bahwa dia sedang menikmati masakan di warung lalu bersenandung bersama para penyanyi jalanan dalam interaksi yang guyub, sinyal yang ditebarkan Jokowi adalah: kebahagiaan itu murah untuk meraihnya, tak mesti memperolehnya di tempat eksklusif dan di kancah musisi elitis.
Tentu semua kiprah pamer kesederhanaan bukan yang paling signifikan dari seorang pemimpin politik. Semua itu bisa dikemas oleh sutradara. Yang esensial dari seorang pemimpin jelas kesanggupannya untuk merealisasikan keadilan di tengan tarik-menarik kepentingan yang bertabrakan di hadapan sang pemimpin.
Ketika sang pemimpin berani menampik bujukan kelompok elite paling berpengaruh untuk meluluskan kepentingan mereka dan konsisten meluluskan kepentingan rakyat yang terpinggirkan karena tak punya suara dan daya membujuk, saat itulah keistimewaan pemimpin yang sejati mulai mengejawantah.
Namun politik tak beroperasi dalam mekanisme yang simplistik lurus lempang. Kebijakan yang prorakyat kecil pun bisa menjadi jalan masuk bagi kaum elite untuk menikmati alokasi dana yang dijatahkan buat rakyat kecil kebanyakan.
Kesanggupan mencegah distorsi mengalirnya kue pembangunan yang sesungguhnya untuk rakyat bawah akan menjadi barometer seberapa sukses seorang pemimpin politik.
Tampaknya, di titik inilah Jokowi masih harus bekerja keras untuk meminimalkan para politikus yang separpol dengannya terlibat dalam pesta-pora menikmati dana negara dengan melawan undang-undang.
Ketika SBY berkuasa, tak sedikit politikus Partai Demokrat yang terjerat skandal penggangsiran uang rakyat sehingga di kemudian hari mereka terjeblos ke dalam penjara.
Dengan demikian, kurang esensiallah pertama-tama mengukur kebesaran pemimpin politik dari sisi seberapa hebat dia menelurkan pikiran-pikiran.
Tampaknya, di titik inilah Jokowi masih harus bekerja keras untuk meminimalkan para politikus yang separpol dengannya terlibat dalam pesta-pora menikmati dana negara dengan melawan undang-undang.
Ketika SBY berkuasa, tak sedikit politikus Partai Demokrat yang terjerat skandal penggangsiran uang rakyat sehingga di kemudian hari mereka terjeblos ke dalam penjara.
Dengan demikian, kurang esensiallah pertama-tama mengukur kebesaran pemimpin politik dari sisi seberapa hebat dia menelurkan pikiran-pikiran.
Barangkali yang justru lebih perlu diukur adalah: seberapa berhasil pemimpin politik itu mewujudkan pikiran-pikiran hebat dari mana pun datangnya sehingga dia sanggup menyejahterakan rakyat yang belum sejahtera.
Apalagi saat ini sudah terlalu banyak pikiran yang cemerlang. Berbagai pakar berbagai bidang di seluruh dunia menelorkan pikiran-pikiran cemerlang di jurnal-jurnal kaliber internasional, yang bisa dipungut untuk dijadikan landasan pengambilan kebijakan kenegaraan.
Jadi tak perlulah menuntut Jokowi untuk melahirkan pikiran-pikiran yang bisa dibanggakan oleh kalangan akademikus. Lebih perlu untuk mendesak sang Presiden mewujudkan apa yang selama ini belum terwujud, namun menjadi impian semua orang. (Ben/An)
Apalagi saat ini sudah terlalu banyak pikiran yang cemerlang. Berbagai pakar berbagai bidang di seluruh dunia menelorkan pikiran-pikiran cemerlang di jurnal-jurnal kaliber internasional, yang bisa dipungut untuk dijadikan landasan pengambilan kebijakan kenegaraan.
Jadi tak perlulah menuntut Jokowi untuk melahirkan pikiran-pikiran yang bisa dibanggakan oleh kalangan akademikus. Lebih perlu untuk mendesak sang Presiden mewujudkan apa yang selama ini belum terwujud, namun menjadi impian semua orang. (Ben/An)
M. Sunyoto
Tags
Sosial Politik